Bola.com, Jakarta - Mendukung tim sepak bola yang bergelimang trofi, berlembar-lembar kisah sukses, dan berisi pemain-pemain kelas dunia tentu menyenangkan buat banyak orang. Menikmati kemenangan pada akhir pekan jadi satu di antara sekian cara menutup penatnya hiruk pikuk pekerjaan atau rutinitas sehari-hari. Lalu apa kabar pencinta kesebelasan gurem yang tiap pekannya dihantui hasil minor?
Buat fans tim-tim medioker di luar sana, tentu ada ikatan batin yang sudah terjalin sejak lama, yang sukar dilogikakan. Local pride sebutannya, atau apalah itu. Tengok saja suporter Sunderland yang jika bukan karena pandemi corona, sudah pasti memenuhi Stadium of Light meski timnya sudah lama terjerembab di kasta bawah Liga Inggris, berharap bisa kembali ke Premier League dan bertemu rivalnya, Newcastle United.
Baca Juga
Advertisement
Leeds United jadi contoh lainnya. Enam belas tahun lamanya berjuang demi kembali ke Premier League, terbayar tuntas dengan sukses juara Championship Division. Suporter jadi pihak yang paling berbahagia. Doa, dukungan, penantian, dan harapan untuk kembali memetakan diri di sepak bola terbaik Liga Inggris menuai hasil.
Padahal, mereka berhak untuk mendukung 'tim besar' di Inggris. Sama dengan suporter sepak bola di Spanyol, Jerman, Prancis, Brasil, negara manapun, termasuk Indonesia. Tapi ada pride tersendiri yang membuat mereka teguh untuk tetap mendukung tim yang mereka yakini adalah tim terbaik, sekalipun meraih hasil imbang melawan penguasa kompetisi saja sudah seperti kemenangan besar.
Ada satu kesamaan di antara para pendukung tim gurem, yakni mereka mencintai sepak bola dengan cara yang tidak pernah mereka kira, dan mereka tidak peduli status dan kualitas klub yang mereka cintai di atas kertas.
Penulis membaca sebuah situs olahraga di Irlandia beberapa saat setelah undian babak grup Liga Champions. Dalam laporan ringannya, tertulis kekecewaan besar, bukan karena Dundalk, tim sepak bola Irlandia, bertemu dengan lawan kuat Arsenal, melainkan karena tipisnya peluang suporter menyaksikan langsung laga tersebut di kandang mereka akibat pandemi corona.
Begitu besarnya passion suporter Dundalk bertemu Arsenal, meski di atas kertas kekuatan kedua tim bertolak belakang. Mereka seakan menomorduakan hasil akhir, yang terpenting klub kesayangan mereka bisa bersaing di pentas tertinggi antarklub Eropa, terlebih lawannya adalah wakil dari Inggris, tetangganya sendiri. Mungkin, kemenangan hanyalah bonus, sementara gairah mendukung adalah luapan emosi yang tak ternilai harganya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3259787/original/056505200_1602020880-WHUFC9.jpg)
Penulis tidak mau menyematkan Newcastle United sebagai tim gurem, tapi saya ingin me-relate perasaan fans The Toon dengan seni mendukung tim gurem. Soal prestasi, Newcastle pernah berjaya di Liga Inggris, sama seperti Leeds United. Jadi, saya lebih suka melabeli klub ini sebagai tim medioker jika titel tim gurem terlalu berlebihan.
Berbanding terbalik dengan tim-tim yang mapan, baik secara finansial maupun struktur organisasi, Newcastle United bisa dibilang adem-adem panas. Adem karena keuangan klub terbilang stabil, namun panas karena pengelolaan yang bikin gemas suporternya. Ini terjadi setelah Mike Ashley masuk sebagai pemegang saham klub pada 2007.
Ketika suporter Newcastle United berharap banyak pada Mike Ashley, mereka justru dibuat kecewa karena belakangan pria berusia 56 tahun ini malah terkesan ogah-ogahan mengelola klub. Tiga kali sudah ia berniat menjual Newcastle, meski pada kesempatan ketiganya lebih karena didesak oleh suporter. Alih-alih, kesepakatan dengan Arab Saudi justru kandas karena campur tangan Premier League dan Badan Amnesti Internasional, dan suporter harus bersabar lagi menanti Mike Ashley angkat kaki dari St. James' Park.
Manchester United juga memiliki persoalan mirip dengan Newcastle dan West Ham yang bermasalah dengan pemilik klubnya. Suporter di Manchester sono begitu vokal menyuarakan mosi tidak percaya kepada Glazer Family. Toh, pada akhirnya, yang terpenting buat suporter yang bukan asli Inggris adalah MU bisa menang supaya terhindar dari sindiran suporter klub lain.
Ada kedekatan unik nan intim yang terjalin ketika mendukung tim gurem. Informasi mengenai tim kesayangan menjadi lebih direct ketimbang mendukung tim besar. Ketimbang hanya menemui pembahasan soal strategi, pemain idola, dan hal-hal teknis lainnya, yang ujung-ujungnya saling sindir lewat meme kocak, Anda bisa tenggelam lebih dalam sampai ke 'dapur' klub.
Di sinilah seninya. Ada ikatan yang secara tak sadar muncul begitu saja. Ibarat orang yang sedang jatuh cinta, Anda jadi ingin mengetahui informasi apa saja soal si dia, baik dan buruknya. Kemudian dengan sendirinya rasa cinta itu akan tumbuh menjadi unconditional love, bahwa Anda akan mencintai sebuah klub apa adanya, tanpa alasan, tanpa logika, bahwa Anda menginginkan yang terbaik buat klub yang Anda cintai.
Dalam tulisan ini, penulis bukannya mau mengecilkan passion fans tim-tim besar. Tentu saja tiap orang punya alasan. Sebagian orang menilai bahwa sepak bola hanyalah olahraga. Tapi tak sedikit yang merasa jika permainan si kulit bundar lebih dari itu. Bill Shankly pernah berkata:
"Some people think football is a matter of life and death. I don't like that attitude. I can assure them it is much more serious than that,"
Video
Eks Real Madrid, Julian Faubert, bermain tanya jawab cepat dengan redaksi Bola.com
Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)
Soal Selera
Penulis sering mendapat pertanyaan, "Kenapa suka West Ham?". Pertanyaan ini sama ngeselinnya kalau Anda ditanya: "Kenapa mau sama dia?" Sebab, makin besar cinta Anda, maka akan makin sulit menjawabnya. Inilah yang dinamakan unconditional love. Anda jadi tidak peduli dan ujung-ujungnya akan menjawab, "Ya suka aja".
Namun demikian, rasanya bohong banget jika tidak ada alasan utama di balik rasa cinta saya dan pendukung West Ham lainnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3259790/original/031667300_1602021043-WHUFC5.jpg)
Penulis secara pribadi sudah suka sepak bola sejak kecil. Pemain idola pertama saya adalah Andriy Shevchenko. Saya masih ingat jersey pertama saya yang dibelikan ayah, yakni seragam Timnas Kroasia, Jerman, dan Denmark. Waktu itu saya belum punya tim favorit, baru sebatas pemain idola saja. Teman-teman SD pun sama, condong suka pemain ketimbang klubnya. Tidak heran ketika aktif di SSB, kami mencoba meniru gaya bermain si pesepak bola idola, bahkan sampai sepatu dan gaya rambutnya.
Poster sepak bola yang bisa didapatkan melalui tabloid olahraga seperti Tabloid BOLA dan Soccer menjadi harta karun saat itu. Belum lagi abang-abangan yang menjual poster edisi Piala Dunia 1998, biarpun kualitasnya jelek, tetap saja menjadi incaran anak-anak seusia saya.
Siaran langsung sepak bola di televisi sudah mulai ramai, Liga Italia dan Liga Inggris jadi magnet. Lagi-lagi, belum ada ketertarikan dengan sebuah tim. Saya hanya menyukai pemain-pemainnya saja. Selain Andriy Shevchenko, saya juga suka Bernardo Corradi, Mike Hanke, Thomas Lincoln, Freddie Ljungberg, sampai Carsten Ramelow.
Mungkin, generasi penulis adalah generasi di mana anak-anak lebih menikmati aksi individu pemain ketimbang keindahan permainan sepak bola secara tim. Kecenderungan lain yang saya rasakan saat itu adalah mendukung tim-tim yang 'struggling', entah kenapa, saya sendiri heran.
Penulis bisa begitu bahagia menyaksikan Chievo misalnya, mengalahkan Juventus, Milan, Inter, atau Fiorentina. Juga suka mengamati bagaimana AZ Alkmaar mendobrak dominasi Ajax, PSV, dan Feyenoord.
Kalau boleh disimpulkan, saya tidak suka mendukung tim-tim yang dominan menguasai liga atau kompetisi. Ada kepuasan yang didapat ketika melihat pemain dan suporter tim gurem berhasil meraih kemenangan atas tim besar. Sama halnya dengan MotoGP dan F1: sekali-kali tak ingin melihat Valentino Rossi atau Michael Schumacher yang menang, menang, dan menang lagi.
![]()
Semuanya lalu terjadi pada 2006-2007. Jelang akhir musim, West Ham United di ambang degradasi. Lawan terakhirnya adalah Manchester United yang sudah dipastikan juara. West Ham, seperti biasa, berkutat di papan bawah. Alan Pardew sudah dipecat, digantikan oleh Alan Curbishley. The Hammers butuh kemenangan. Bukan perkara mudah, sebab itu harus dilakukan di Old Trafford.
Mukjizat itu datang melalui sentuhan Carlos Tevez. West Ham lolos dari jeratan degradasi. Musim itupun dijuluki The Great Escape dan menjadi satu di antara musim buruk paling berkesan. Dari sanalah semuanya bermula, "Yes, akhirnya awakku punya juga first team yang didukung sampai sekarang dan tentu buat seterusnya."
Mendukung sebuah tim adalah soal selera. Kebetulan selara penulis adalah West Ham, tim yang dibuat oleh pekerja galangan kapal, yang entah kapan bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Sudah cukup bahagia rasanya melihat The Hammers meraup satu poin dari klub elite macam Liverpool, Manchester United, Manchester City, Chelsea, atau Tottenham Hotspur.
Advertisement
Hipster? Alah, yang Penting Konsisten!
Risiko mendukung tim gurem adalah cap hipster. Risiko ini sebenarnya sama besarnya buat mereka yang mendukung tim besar, yakni dengan sebutan glory hunter. Fair ya? Fair dong!
Penulis secara pribadi menyimpulkan bahwa hipster dalam sepak bola adalah kecenderungan orang untuk memilih klub yang tidak popular agar dianggap keren atau anti-mainstream karena kecenderungan tren.
Sama halnya dalam musik, di mana saat sedang ngetren musim indie misalnya, maka berbondong-bondonglah mereka masuk ke scene tersebut, lalu pindah haluan lagi ketika kebetulan tren musik baru datang. Jadi selama konsisten memiliki first team, saya rasa cap hipster tidaklah tepat.
Ngomong-ngomong soal musik, siapa sangka fanbase West Ham di Indonesia memiliki cerita unik. Kecintaan terhadap aliran musik Oi! Punk mempertemukan pendukung West Ham di Jakarta yang akhirnya terbentuklah Jakarta Hammers, meski saya yakin tidak semuanya karena musik. Hal serupa juga terjadi di kota-kota lain, seperti Depok, Bekasi, Bogor, Semarang, Solo, hingga Malang.
Panjang jika harus meruntut keterkaitan musik dengan West Ham. Tapi, saya yakin West Ham adalah satu dari sedikit klub sepak bola yang punya afiliasi sangat dekat dengan musik. Beberapa band legendaris dari era 1970-an seperti Cockney Rejects, Cock Sparrer, Morissey hingga band-band 2000-an seperti Booze and Glory dikenal sering memperlihatkan kecintaannya terhadap West Ham.
Dari sana, penggemar band-band tersebut mengetahui bahwa ada afiliasi yang terbentuk antara band idolanya dengan West Ham, dan kemudian mereka 'mendeklarasikan' kecintaannya terhadap The Mighty Hammers. Maka jangan heran kalau banyak fans West Ham di Indonesia khususnya, datang dari latar belakang scene skinhead dan punk.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3259791/original/039270900_1602021067-WHUFC1.jpg)
Selain itu, ada juga anggapan kalau mendukung West Ham adalah way of life. Seperti tadi sudah disebutkan, West Ham kental dengan nuansa working class. Logo palu silang menunjukkan hal tersebut. Di sisi lain, scene punk atau skinhead kental dengan stigma working class. Mereka mungkin melihat West Ham mewakili ideologi yang mereka anut.
Salah? Tentu tidak. Ini soal selera, Bung!
Ada banyak alasan kenapa mereka memilih West Ham sebagai tim idola. Fenomena film Green Street Hooligans juga sedikit banyak memengaruhi orang jadi fans The Hammers, kok. Sah-sah saja. Cinta bisa datang dari mana saja, kan? Yang penting konsisten.
Harga yang Tak Terbayarkan
Mendukung tim gurem seperti West Ham penuh dengan suka duka. Penulis punya cerita seru yang terjadi pada 2012 silam. Saya yang tinggal di Semarang mencoba menjalin komunikasi dengan sesama fans West Ham. Lalu saya bertemu dengan seorang teman, Ical panggilannya.
Kami memutuskan untuk bertemu dalam sebuah acara nonton bareng, waktu itu Liverpool Vs West Ham. Saya mengontak Big Reds Semarang dan meminta izin untuk bergabung. Bisa dibayangkan, saya yang cuma berdua dengan teman saya diapit oleh lusinan pendukung setia Liverpool.
Semarang Hammers kemudian dicetuskan, meski saya sangat yakin sebelumnya sudah ada banyak penggila West Ham di Kota Loenpia tersebut, hanya saja belum terkoordinasi dengan rapi. Seringkali saya nonbar hanya berdua saja, paling banyak enam orang.
Tidak ada istilah membership, tidak ada ketua, yang ada hanya divisi ketawa.
"Wayah nonbar kowe teko, pesen ombenan opo panganan, mbayar. Rak duwe duit ngomong, tak bayari nge-beer. Enggak penting menang, enggak penting kalah, yang penting mabuk!"
Perlahan tapi pasti, kami dari yang awalnya berdua saja, berkembang jadi empat, delapan, 20, sampai entahlah sekarang berapa. Peran suporter klub lokal PSIS Semarang juga punya andil meramaikan. Benar dugaan saya, pasti ada banyak.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3259788/original/069452400_1602020908-WHUFC8.jpg)
Berbeda dengan klub lain, menjadi suporter fanatik West Ham bisa bikin gelo. Sulit mencari atribut berbau West Ham, mulai dari jersey sampai scarf. Dulu jarang ada jersey KW. Setidaknya, itu bisa kami banggakan saat nonbar, karena kami 'tampil original' dari atas sampai bawah, dari luar sampai dalam.
Sebut kami Hooligans Livescore karena sulitnya mendapatkan akses siaran langsung, baik di tv lokal maupun channel berbayar. Sekalinya ada, untuk booking tempat nonbar tidak serta merta dibolehkan.
"Anggotanya ada berapa Mas? Kalau sedikit nuwun sewu Mas, kami enggak bisa kasih."
Respons seperti itu sering kami terima. Pada akhirnya, kami kadang berkumpul di satu tempat, beli congyang, ngobrol ngalor-ngidul, sembari ngamati lini masa Twitter atau livescore. Kalau ada cafe yang mempersilakan kami nonbar, karena jumlahnya tidak banyak, kesannya malah mengganggu pasangan muda-mudi yang sedang berpacaran. Mereka risih, lalu pergi, dan kami merayakannya seperti suporter merayakan gol.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/3259786/original/020768900_1602020834-WHUFC10.jpg)
Pada satu momen, penulis mendapatkan email dari salah satu staf klub West Ham. Mungkin, beliau sering memperhatikan aktivitas kami di media sosial Twitter terkait West Ham di Indonesia, sampai akhirnya beliau menghubungi saya lewat e-mail.
Tidak disangka, komunikasi penulis dengan beliau dijadikan sebuah artikel khusus di situs resmi West Ham. Buat pendukung tim gurem yang tak pernah merasakan langsung atmosfer Boleyn Ground sampai dirubuhkan dan pindah ke London Stadium, ini menjadi sebuah kebanggaan. Gile cing, cerita soal kami sampai juga ke London!
Mungkin inilah seni mendukung tim gurem, yang tidak cuma terpaku pada hasil akhir, statistik, dan trofi. Lebih dari itu, bisa terlibat secara intim, berinteraksi langsung dengan para fans West Ham asli dari Inggris, ikut memperjuangkan nasib klub, mungkin jadi harga yang tak pernah terbayarkan.
Advertisement
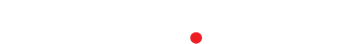 bola
bola:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1315985/original/060371500_1471001883-0245c7b36ca9fd9cf4f34632bf2d8588-082263200_1469609900-000_DI2LW.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1409803/original/055774900_1479463912-manchester-united.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1316037/original/089486600_1471003693-Chelsea_FC.svg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1316067/original/044091200_1471006308-Liverpool_FC.svg.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3259469/original/057345100_1602050671-Cerita_Bola_-_West_Ham_United__Logo__Pemain__dan_Suporternya.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3259783/original/087074300_1602020567-WHUFC3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3259784/original/094666100_1602020682-WHUFC2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3259785/original/012284300_1602020737-WHUFC11.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5008239/original/092876300_1731704437-20241116BL_Hubner_dan_Endo_3.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4999088/original/050835500_1731297593-000_36LZ3P7.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/345172/original/097862000_1460355557-FullSizeRender.jpg)
/kly-media-production/medias/4867115/original/044986200_1718717026-Liga_Inggris_-_Ilustrasi_Logo_dan_Piala_Liga_Inggris_2024_2025_copy.jpg)
/kly-media-production/medias/5016929/original/086386300_1732246517-ATK_Bola_EPL_2025_Schedule_MW_12.jpg)
/kly-media-production/medias/5011228/original/021555800_1731972048-GcsM88BXwAAlvJg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4980842/original/004446300_1729950244-IMG-20241026-WA0012.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016081/original/008305700_1732181405-BRI_Liga_1_-_Persib_Bandung_Vs_Borneo_FC_-_Duel_Pelatih_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016097/original/033305300_1732181807-BRI_Liga_1_-_Persib_Bandung_Vs_Borneo_FC_-_Duel_Mesin_Gol_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3928901/original/045531800_1644407199-BRI_Liga_1_-_Persebaya_Surabaya_Vs_Persija_Jakarta.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4946179/original/041879200_1726575903-Snapinsta.app_460237407_18253148698270592_3021367259501321914_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4890375/original/005197100_1720795966-Electric.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4885554/original/041240400_1720393575-megawati-hangesti-164d27.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4884578/original/006696600_1720245993-komentar-sby-setelah-nonton-langsung-jakarta-lavani-allo-bank-electric-di-pln-mobile-proliga-2024-7032c2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4829539/original/021527900_1715526142-WhatsApp_Image_2024-05-12_at_21.06.33.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4822780/original/050160200_1714967156-Screenshot__5_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4820069/original/051022200_1714667979-Tiket_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4133522/original/078357700_1661278717-AP22234729019791.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5000698/original/011130900_1731319297-Manchester_United_-_Ruben_Amorim_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4527705/original/018558300_1691308891-AP23204483145404.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4867115/original/044986200_1718717026-Liga_Inggris_-_Ilustrasi_Logo_dan_Piala_Liga_Inggris_2024_2025_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016929/original/086386300_1732246517-ATK_Bola_EPL_2025_Schedule_MW_12.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5011228/original/021555800_1731972048-GcsM88BXwAAlvJg.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012352/original/034239500_1732025658-IMG_2639.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4800580/original/043980900_1712980850-emil.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4937699/original/074316600_1725571518-4_Garuda._Mendunia.________KitaGaruda______TimnasDay__6_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014662/original/053932700_1732102817-Timnas_Indonesia_-_Marselino_Ferdinan__Rizky_Ridho__Calvin_Verdonk_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014187/original/025735900_1732086673-20241119AA_Indonesia_vs_Arab_Saudi__70_of_110_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4969963/original/059345200_1729006746-000_36K43ND.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/765871/original/088174700_1415886345-Irfan_Bachdim.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1234673/original/000622700_1463386120-_20160514NH_Manahati_Lestusen_PS_TNI_M_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1298659/original/099791800_1469523526-wawancara_Rizky_R.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1289665/original/065058700_1468594570-20160715AB_Azwan_Karim_03.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1125195/original/005248400_1453966510-_20160127NH_Andik_dan_medali_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1295978/original/075250800_1469206051-_20160722NH_Hansamu_Yama_Barito_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5016036/original/064843400_1732179830-4-pelatih-yang-bisa-mengambil-alih-kursi-carlo-ancelotti-di-real-madrid-526bde.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5016836/original/041973700_1732242023-1120-02a8a1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5015934/original/072753400_1732176741-ketemu-pemain-timnas-1-5deaeb.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5016448/original/099532500_1732200085-pep-guardiola-segudang-masalah-f602e2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5016433/original/037226900_1732199100-draft-2-88ddd2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5014896/original/026932300_1732114812-bola-break-arab-saudi-biasa-saja-ah-timnas-indonesia-layak-menang-ef2edb.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5014873/original/065229300_1732113105-image_50445057.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015232/original/096331900_1732154573-20241119IQ_Timnas_IndonesiavsArab_Saudi-56.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5010894/original/033436700_1731938028-Konpers_Timnas_Indonesia-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016792/original/075603200_1732238330-Calvin_Verdonk-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015368/original/050795400_1732160028-image_123650291__1_.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5012274/original/044761400_1732021187-20241119AA_Indonesia_Vs_Arab_Saudi-15.JPG)