Bola.com, Jakarta - "Film loe selanjutnya sepak bola lagi?" tanya seorang kawan dan banyak orang lainnya pada saya, setiap mereka bertanya apa lagi yang sedang saya siapkan kini. Dalam hati agak sebal mendapat pertanyaan seperti itu, bukan karena tentang apa yang sedang saya kerjakan, tapi lebih ke persoalan apakah mereka pikir bahwa ada hal yang spesial dari sepak bola.
Film panjang pertama saya, The Jak (2007), adalah dokumenter tentang suporter sepak bola di ibu kota Indonesia, tentang warga Jakarta yang berkisah tentang kotanya yang berlari terlalu kencang bagi mereka. Tentang simbol dan identitas yang hilang dari diri mereka. "Sebuah esai tentang Jakarta," tulis Totot Indrarto seorang reviewer film top saat itu, yang kini telah menjelma menjadi anggota Dewan Kesenian Jakarta.
Baca Juga
10 Pemain Berpenghasilan Tertinggi di Dunia, Cristiano Ronaldo Kalahkan Lionel Messi dan 3 Superstar Liga Inggris
5 Pesepak Bola yang Paling Kotor Permainannya: Gigitan Luis Suarez Paling Fenomenal
4 Kejutan Menghebohkan Sepanjang Pagi Tadi: Bolivia dan Venezuela Berjaya, Timnas Indonesia dan Inggris Nyesek Bareng
Advertisement
Karya panjang kedua saya lagi-lagi dokumenter, The Conductors (2008), yang secara komersial pernah tayang di daerah perdagangan Iberia dan Eropa Tengah, bagi Totot adalah "Sebuah esai tentang kepemimpinan," yang saya buat dengan perspektif bahwa pemimpin sejati adalah seseorang yang diinginkan oleh khalayaknya.
Lalu saat saya membuat karya fiksi pertama dan film ketiga saya, Romeo Juliet (2009), alm. Alex Komang berkomentar tentang naskahnya "Fanatisme adalah hal yang baik jika disimpan untuk diri, namun akan mengganggu jika harus dibagikan pada banyak orang lain." Lalu berkisahlah ia tentang perusakan tempat ibadah, pembakaran tempat hiburan hanya karena para fanatik ingin berbagi rasa fanatiknya pada orang lain.
Agak mundur ke belakang di tahun 2005 saat Hardline (2005), salah satu dokumenter pendek pertama saya, menjadi wakil Indonesia di kumpulan film pendek untuk Piala Dunia 2006 di Jerman. Chairman Berlinale Talent Campus, Dieter Kosslick berkomentar "Menarik untuk melihat bahwa di Jakarta kebutuhan akan ruang menjadi sangat penting, padahal kita melihat banyak gedung besar di sana, tapi mereka tampak kehilangan ruang terbukanya."
Lalu bagian mana dari film saya yang sepak bola? Memang sepak bola selalu saya jadikan sebagai latar dari cerita, seperti Christopher Nolan selalu menjadikan filsafat dan psikologi sebagai latar atau Martin Scorcese menjadikan kekerasan sebagai latar penceritaannya. Sepak bola adalah permainan terpenting di negeri ini sementara permainan lain praktis luput dari perhatian. Popularitasnya yang luar biasa di negeri ini membuat permainan ini menyatu dengan baik pada diri kita, seperti agama yang pada bangsa ini seolah menjadi budaya. Maka saya pikir sah saja menjadikannya latar cara bercerita.
Walau kemudian saya salah, karena Indonesia bukanlah negeri olah raga. Olah raga di negeri ini adalah bahan tontonan saja, atau kegiatan selebrasi 17 Agustus yang ramai dimainkan di kelurahan sampai RT. Demikian banyaknya cabang olah raga, dalam kurun 50 tahun terakhir tak ada lebih dari empat film tentang bulutangkis (cabang olah raga yang rutin memberi kita gelar) tak lebih dari sembilan yang berlatar atau tentang sepak bola dan dua berlatar atletik (itupun lari jarak jauh semua)
Cabang olah raga lain? Wah mengingat saja rasanya susah. Saya agak susah mengingat ada film dengan latar atau kisah basket, gulat, voli, silat atau bahkan tinju (Opera Jakarta dari tahun 1980 mungkin bisa dikategorikan berlatar tinju). Jadi lalu saya memang harus berbesar hati dan menerima saja bahwa latar yang saya buat praktis adalah hal yang memang tidak dikerjakan banyak orang lainnya.
Bagi saya 2 film panjang pertama saya adalah dokumenter biasa. Romeo Juliet adalah action-love story, lalu Hari Ini Pasti Menang (2013) adalah intrik politik dan kekerasan yang biasa terjadi di dunia olah raga. Kemudian Garuda 19 (2014) lah sejatinya film sepak bola seperti yang biasa orang labelkan pada saya.
Berada di tatanan masyarakat yang hanya memahami olah raga sebagai sekadar kegiatan kesehatan atau gaya hidup memang membuat ruang menjadi sangat terbatas. Olah raga bukanlah sesuatu yang dibicarakan dan dikaji secara sosiologis, namun dikerjakan dan saat selesai di post di media sosial. Padahal olah raga adalah sebuah kegiatan yang punya makna filosofis besar. Contohnya, marathon terjadi karena seorang kurir berlari sejauh 42,195 km demi mengantarkan surat perdamaian.
Sepak bola muncul sebagai bentuk pemujaan kaum Aztec pada matahari atau bangsa India mengklaim sebagai perlawanan Khrisna terhadap Sharvakanak saat ia masih muda. Polo lahir saat bangsa Bangladesh atau Afghanistan memacu kuda mereka mengejar buruan dan seterusnya dan seterusnya. Kegiatan penciptaan permainan itu sendiri memiliki makna yang luar biasa, sayangnya kita tidak pernah berada pada cara berpikir seperti itu karena secara kebanyakan bangsa kita memang berada pada budaya yang meloncat yaitu ‘melihat dan kemudian meniru’. Kita lupa pada membaca, menelaah, dan memahami.
Jadi jangan heran jika Amerika pernah mampu melahirkan sebuah kisah golf yang sangat indah bagai puisi lewat Legend of Bagger Vance (2000) atau Inggris pernah memotret biografi sosok keras kepala dengan cara yang keras pula lewat Damned United (2009) atau buku-buku kajian olah raga mereka lewat perspektif budaya, sosiologi bahkan sastra (suatu saat akan saya review buku Footbal in Sun and Shadow nya Eduardo Galeano yang dahsyat itu) maka kita terus saja berhenti pada pemujaan sosok atau sekedar pertunjukan kisah sukses seseorang di bidang ini.
Jika saja olah raga di negeri ini bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari karya sastra ataupun kajian lainnya, saya yakin posisi pertama di SEA Games itu tak akan pernah lagi lepas dari kita.
Andibachtiar Yusuf
Filmmaker & Constant Traveller
@andibachtiar
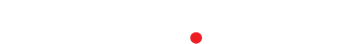 bola
bola
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/915707/original/050575400_1435751449-KOLOM-ANDIBACHTIAR-YUSUF.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/337821/original/058832000_1460136394-Anugraheni_Prasetyaningjati.jpg)
/kly-media-production/medias/4965305/original/000634600_1728544546-Penonton_Timnas_di_GBK.jpg)
/kly-media-production/medias/4441615/original/076902800_1685051474-000_33G933Q.jpg)
/kly-media-production/medias/3105794/original/072825500_1587198832-FotoJet__2_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5021013/original/060621500_1732550807-RILIS_OKS-1.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4902911/original/085000800_1722090982-Persib_Bandung_-_Ilustrasi_Logo_Persib_Bandung_2024_copy.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4836013/original/035216500_1716046719-20240518AA_Pertandingan_Liga_1_Persib_Bandung_Vs_Bali_United-15.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4042591/original/058261400_1654335994-285425692_154691467115939_1209437247413352747_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5004299/original/056911600_1731504389-083A7842.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4998749/original/053166700_1731258516-Yakob___Yance_Sayuri.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4890375/original/005197100_1720795966-Electric.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4885554/original/041240400_1720393575-megawati-hangesti-164d27.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/4884578/original/006696600_1720245993-komentar-sby-setelah-nonton-langsung-jakarta-lavani-allo-bank-electric-di-pln-mobile-proliga-2024-7032c2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4829539/original/021527900_1715526142-WhatsApp_Image_2024-05-12_at_21.06.33.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4822780/original/050160200_1714967156-Screenshot__5_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4820069/original/051022200_1714667979-Tiket_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4962185/original/062030900_1728296003-000_36H78QK.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5020849/original/041246100_1732538070-aksi-heroik-moh-salah-cc5a40.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020541/original/080367400_1732525848-000_36N87ZU.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4998892/original/068863400_1731289702-AP24315584455357.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019813/original/090837200_1732486036-AP24329568887644.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020463/original/090712300_1732523344-Liverpool_Mohamed_Salah-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5008160/original/023821700_1731693104-20241115AA_Indonesia_Vs_Jepang-07.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4967178/original/005767300_1728726762-Snapinsta.app_443006345_425096636972342_5354630664133235363_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019646/original/026040200_1732455663-GdJgF09XcAAoT7R.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019532/original/016802100_1732446164-SaveVid.Net_449339498_17928877625866389_850118387571268346_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4876364/original/099249900_1719465777-Latihan_Timnas_Putri_Indonesia__4_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019346/original/051946600_1732425765-SaveVid.Net_468182095_1308913556954079_5159327323408827674_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/765871/original/088174700_1415886345-Irfan_Bachdim.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1234673/original/000622700_1463386120-_20160514NH_Manahati_Lestusen_PS_TNI_M_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1298659/original/099791800_1469523526-wawancara_Rizky_R.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1289665/original/065058700_1468594570-20160715AB_Azwan_Karim_03.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1125195/original/005248400_1453966510-_20160127NH_Andik_dan_medali_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1295978/original/075250800_1469206051-_20160722NH_Hansamu_Yama_Barito_01.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5019415/original/038931400_1732433415-1000013427-c6ce80.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5020208/original/006365800_1732512970-moh-salah-pahlawan-0f407d.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5020146/original/059291300_1732509405-mu-ditahan-imbang-3cd95f.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5020084/original/059245600_1732506148-wisata-belem-52ccc7.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5016036/original/064843400_1732179830-4-pelatih-yang-bisa-mengambil-alih-kursi-carlo-ancelotti-di-real-madrid-526bde.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019139/original/042222300_1732403375-Museum_Sporting_CP-5.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5020422/original/086459100_1732521703-Manchester_United_Debut_Ruben_Amorim-1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5016792/original/075603200_1732238330-Calvin_Verdonk-2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5015232/original/096331900_1732154573-20241119IQ_Timnas_IndonesiavsArab_Saudi-56.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5019592/original/015473300_1732451094-image_123650291__3_.JPG)